TUHAN BARU DI ERA MEDSOS, VALIDASI
Sejak lama Tuhan klasik yang menempel di keyakinan masih tersimpan rapi sebagai baju agama. Ketika jaman makin berkembang, kompetisi untuk bertahan hidup makin sengit akhirnya memunculkan tuhan baru, yaitu uang. Lalu teknologi digital makin berkembang, muncul lagi persaingan sengit agar orang bisa menonjol, stand out, dari yang lain. Maka muncullah tuhan baru, yaitu validasi, dimana orang butuh untuk diakui, diacungi jempol, disukai, digandrungi, dielu-elukan.
Di era media sosial ini kita merasa seperti hidup ini seperti kompetisi tak berujung, di mana setiap postingan kita adalah ajang perebutan validasi dan pengakuan. Dari pengumpulan validasi itu muncullah ketenaran dan kesuksesan. Di jaman media sosial seperti sekarang, kebutuhan primer kita seolah sudah bergeser. Bukan lagi makanan, pakaian, atau tempat tinggal, tapi yang lebih utama adalah likes, comments, shares, dan subscribes. Semua itu jadi ukuran “sukses” kita. Tapi, apakah itu benar-benar membuat kita bahagia?
Kita membayangkan media sosial seperti sebuah pesta besar di mana semua orang datang dengan topeng. Kita posting foto liburan mewah, bukan karena ingin berbagi cerita, tapi karena berharap banjir like yang membuat kita merasa “diakui”. Misalnya, ada seseorang yang setiap hari upload story tentang rutinitas kebugarannya. Bukan karena dia benar-benar menikmati prosesnya untuk bugar, tapi karena setiap likemembuatnya merasa lebih “bernilai”, “berhasil”. Lalu apakah komentar dan suka yang dibagikan orang itu semua tulus? Tidak semuanya. Kita menyukai dengan simbol like terhadap postingan orang lain bukan karena suka, tapi karena berharap dibalas like juga nantinya. Semua berpamrih demi validasi dan pengakuan atau rekognisi. Dunia media sosial ini seperti pasar malam. Pengakuan, validasi, suka, komentar itu seperti transaksi. Kita tukar-menukar perhatian dengan pamrih, tapi tak ada yang benar-benar kenyang. Saya kadang termasuk golongan ini. Posting, pamer, dengan pamrih diperhatikan dan diberi validasi.
Kenapa ini terjadi? Karena otak kita dirancang untuk mencari pengakuan sosial, seperti zaman purba di mana kelangsungan hidup bergantung pada kelompok suku. Tapi sekarang, algoritma media sosial memanfaatkan itu. Setiap notifikasi seperti dosis dopamin instan, mirip junk food yang enak tapi tak bergizi. Lama-lama, kita lupa bahwa relasi tulus itu seperti makanan sehat. Semua butuh waktu, usaha, dan tak selalu instan. Ibarat pohon, like itu seperti daun yang gugur cepat, tapi relasi sejati seperti akar yang dalam dan kuat, menahan badai apa pun.
Tapi jangan khawatir, kita bisa berubah kalau mau. Kita bisa mulai dengan langkah kecil yang memotivasi. Pertama, kita coba “detoks” media sosial. Coba batasi waktu scrolling menjadi 30 menit sehari. Gunakan waktu itu untuk menghubungi teman secara langsung dengan menelepon atau bertemu muka. Saya pernah mencoba ini, dan tiba-tiba relasi dengan sahabat lama menjadi lebih dalam. Bukan lagi soal “berapa like dan follower?”, tapi “apa kabar kamu hari ini?” ini yang jauh lebih bermakna. Kedua, fokus pada nilai hidup yang lebih berharga. Kita bisa mengunggah konten karena memang ingin berbagi inspirasi, bukan mencari pujian, pengikut, atau pamrih lainnya. Kita bisa menulis blog atau mengunggah konten seperti ini karena minat atau passion, bukan karena mencari views, rasanya pasti lebih memuaskan. Memberi tanpa pamrih validasi akan jauh lebih berarti dan membahagiakan.
Validasi sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari layar ponsel. Anda layak bahagia tanpa harus bergantung pada angka-angka jumlah like, follower, view itu. Mari kita bangun relasi tulus, di mana kita saling berbagi dan mendukung tanpa pamrih. Mulai hari ini, lepaskan jerat like dan view, tapi temukan kebebasan dan niat sejati untuk berbagi. Anda bisa, kita semua bisa! Percayalah, Tuhan yang sejati akan rela muncul kembali ketika validasi di medsos tidak lagi dipertuhan dan disembah.***
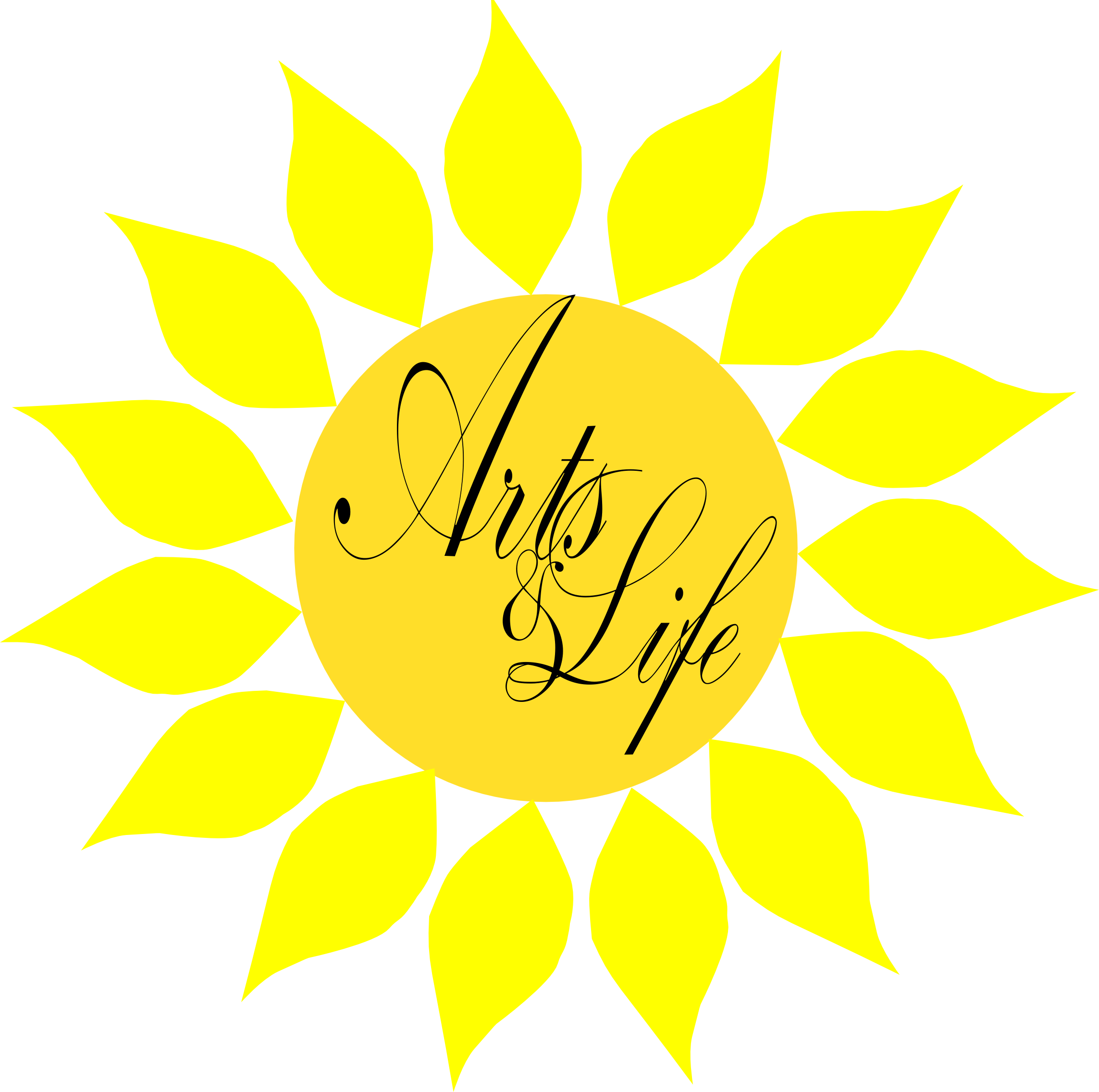

abot iki.. ide melawan kapitalis global..
LikeLike