Teknologi bergerak cepat. Semakin cepat, semakin terkoneksi, semakin dekat, semakin kecil, semakin canggihlah sebuah inovasi teknologi. Itulah yang terjadi dewasa ini.
Di tengah gempuran budaya instan yang dibalut dengan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sebuah proses yang disyaratkan untuk mencapai sesuatu pun dipersingkat. Bahkan penyingkatan itu dipercepat dari hitungan tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit menjadi hitungan detik atau seper sekian detik. Ukuran perangkat pun disulap dari ton, kilogram, gram, dan sekarang nano meter. Inilah budaya instan, sulap menyulap di era modern.
Orang tak lagi mau menunggu sesuatu untuk berproses. Bahkan menunggu akses ke media sosial yang sedang loading, atau buffering, menjadi alasan untuk mengumpat, marah, jengkel, tidak sabaran. Saya yakin pasti Anda semakin sering mengalami. Menunggu beberapa menit atau detik dari sebuah proses sudah cukup untuk memicu nafsu amarah dan uring-uringan. Kata sabar pun sudah makin kabur maknanya, karena hampir semua orang tak mau sabar di era yang bergerak serba cepat ini.
Mau bukti kata sabar itu kabur? Cobalah Anda berdiri di antrean, entah antre membeli makanan, loket pembayaran, di pusat perbelanjaan, di kendaraan, di pom bensin, atau bahkan di tempat ibadah. Pasti tiba-tiba muncul rasa dongkol karena antrean panjang, lama, dan tak bergerak. Dalam hati penuh keluhan, gerutuan. Kata sabar menyingkir jauh dari pikiran.
Di negeri yang katanya religius ini, agama menjadi sentral pengarah moral dan etika. Dari kecil diajarkan bahwa dalam hukum alam, segala sesuatu memerlukan proses. Bahkan Sang Pencipta pun perlu waktu untuk menciptakan ciptaan. Meskipun bisa saja mencipta dalam sekejap mata, sim salabim, langsung jadi. Tapi Dia tidak mengajarkan itu. Buah mangga yang enak pun harus berangkat dari biji, ditanam, dipupuk, tumbuh, dirawat, lalu berbuah. Semua berproses dan ada proses yang harus dijalani. Kalau Sang Pencipta saja sabar menjalani proses, mengapa kita ciptaannya justru sering protes? Ironis, kan.
Saya tidak menyalahkan teknologi, termasuk AI. Perangkat itu dibuat untuk membantu memudahkan semua proses menuju hasil. Tapi, kalau kita akhirnya diperbudak oleh teknologi ciptaan manusia, artinya kita sedang mengorbankan kemanusiaan kita yang wajar, yang selalu berproses. Bukan teknologi, tapi kitalah yang salah mengelola kesadaran kita sebagai manusia.
Seorang atlet yang hebat, peraih medali emas, membutuhkan proses latihan yang panjang dan melelahkan sebelum berlaga. Cendekiawan, ilmuwan, dokter, atau bahkan sang pencipta teknologi, pun menjalani proses panjang, jatuh bangun untuk mengalami kegagalan sebelum berhasil meraih yang diimpikan.
Sayangnya, generasi sekarang yang dimanja oleh teknologi mulai kebanyakan protes daripada berproses. Proses itu dinilai lamban, membuang waktu sia-sia, dan membuka peluang kegagalan. Kesabaran generasi sekarang makin hilang dari kamus hidupnya. Pikiran dan hatinya penuh dengan protes saat berproses. Lihat saja reaksi orang saat menunggu akses medsosnya loading, buffering, atau saat menunggu kuota masuk.
Dalam kehidupan, kita ibaratkan orang yang sedang membangun atau merenovasi rumah, pasti ada proses panjang yang tak mengenakkan yang harus dilakoni. Material rumah didatangkan, ditumpuk, dan mengganggu jalan. Lalu ada bagian rumah yang digempur, diratakan, untuk dibangun kembali. Semua berantakan, berdebu, berisik, mengganggu selama berminggu-minggu. Lama-lama bangunan kelihatan berdiri dengan sentuhan akhir yang halus. Lalu jadilah sebuah rumah persis seperti yang kita inginkan. Ada proses panjang untuk menjadi indah.
Benarlah kata Syaiful Karim, guru ngaji, bahwa proses itu selalu sulit di awal, berantakan di tengah, dan indah di akhir. Sayangnya, kita sekarang selalu protes di saat berantakan. Tak pernah sabar menunggu hasil indah di akhir. Selamat berproses, jangan protes.***(Leo Wahyudi S)
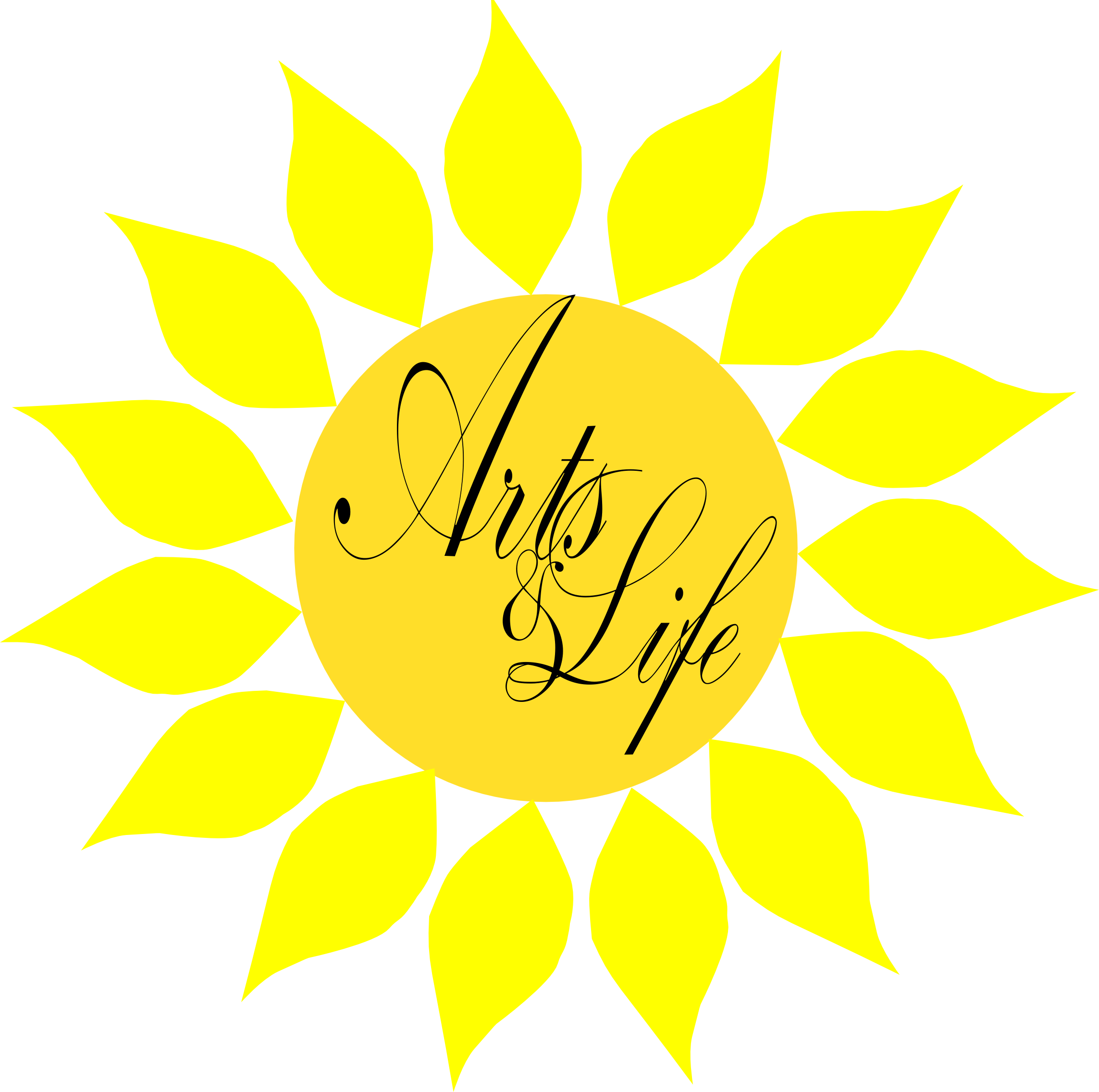

Leave a comment