Pernah suatu kali saya ketemu dengan orang yang baru kenal agama. Ia tetiba menjadi seorang pemeluk agama yang taat, bahkan cenderung fanatik. Gejalanya sudah kelihatan. Ia merasa menguasai aturan, merasa paling benar, merasa paling saleh, paling suci. Sejauh mata memandang hanya berisi penilaian dan penghakiman atas baik dan buruk, suci dan dosa, benar dan salah.
Ia merasa sudah hidup saleh dengan aturan-aturan ketat agama yang dijalaninya. Tak heran urusan-urusan sepele dalam keseharian menjadi sulit gegara belenggu aturan boleh dan tidak, halal dan haram, suci dan dosa, dan sejenisnya. Saya merasa kasihan pada orang itu. Seolah ia menjalani hidup dengan membawa rantai besar yang membelenggu kaki, tangan, mulut, mata, dan telinganya. Agama masih dipahami sebatas aturan pribadi, tanpa ingat bahwa kondisi itu juga berdampak pada kehidupan orang lain. Ia masih sibuk dengan sampul dan tampilan luar agar kelihatan baik dan indah di mata orang dan guru agamanya. Tapi ia lupa mengurusi pikiran dan hatinya agar selaras dengan inti ajaran agamanya. Ironis.
Dengan kata lain, ajaran yang diterimanya mentah-mentah membuat dirinya makin egois, tanpa pernah peduli orang lain. Padahal sependek pengetahuan saya, agama seharusnya menjadi tuntunan kesadaran yang membebaskan seseorang untuk berbuat penuh welas asih, penuh pengetahuan, kebijaksanaan, dan bermuara pada kebenaran.
Orang yang beragama secara sempit akan tinggal di dunia sempit dalam penjara pikirannya. Pikirannya distopia, karena memandang dunia luar yang penuh penderitaan, kesengsaraan, dosa, kemaksiatan, dan segala hal buruk lainnya. Tanpa sadar dunia kita saat ini penuh dengan penjara-penjara kecil,dunia-dunia sempit akibat jeruji pikiran buah dari doktrin, pemahaman, ajaran, yang kurang dicerna dengan kesadaran.
Melihat kondisi ini, Ustad Syaiful Karim mengatakan bahwa pendidikan dan agama harusnya makin membebaskan pikiran dari kebenaran-kebenaran yang dianggap mutlak. Rasa paling benar, paling suci akan menjadi penjara pikiran yang membatasi sehingga dunia menjadi sempit. Akibatnya akan muncul fanatisme, penghakiman, persaingan, dan permusuhan.
Dalam bukunya, Mind-made Prison, Mateo Tabataiy menegaskan bahwa kita adalah pencipta pengalaman diri yang hebat. Kita sangat unggul dalam membentuk, mencetak, dan menciptakan makna. Sayangnya ini menjadi sebuah tragedi kehidupan ketika kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa mereka sejatinya memiliki kekuatan dan potensi luar biasa.
Memang tidak salah kalau kita menciptakan makna atas segala sesuatu. Itu hal wajar yang kita lakukan. Kita bisa menginterpretasikan dunia sesuai keinginan kita sendiri, entah kita suka atau tidak. Hidup merupakan pegalaman internal yang kadang disalahartikan dengan pengalaman eksternal. Artinya, hidup kita ditentukan dari dalam, bukan dari dan oleh pihak luar. Toh kita sesungguhnya tidak melihat dunia luar sebagai sebuah realitas, tetapi hanya dilihat sebagai makna dan interpretasi yang kita pilih. Tidak ada peristiwa negatif atau positif di luar sana. Penilaian positif atau negatif itu adalah makna yang kita ciptakan dalam pikiran kita.
Kita senang menciptakan batasan dan aturan yang pada akhirnya mempersulit hidup kita sendiri. Kita senang menciptakan jeruji-jeruji besi penjara dari pikiran kita. Ironisya, di dalam penjara pikiran yang kita ciptakan sendiri, kita seolah merasa hidup merdeka dengan keyakinan dan kebenaran diri. Di dalam dunia sempit itu kita seolah merasa hebat dan melihat dunia luar yang maha luas dengan muka jijik dan muak.
Kita tidak boleh menjadi narapidana yang terpenjara oleh pikiran dan rekaan kita sendiri. Mari kita tinggalkan dunia sempit yang pengap. Kita narasikan kembali segala ajaran kebaikan dari agama atau dari semesta dengan berpikir yang baik,bertindak baik, penuh welas asih, agar dunia terasa luas dan lapang untuk semua makhluk.***(Leo Wahyudi S)
Foto diambil https://www.theguardian.com/global/2017/mar/19/life-in-a-cuban-jail-for-a-british-man
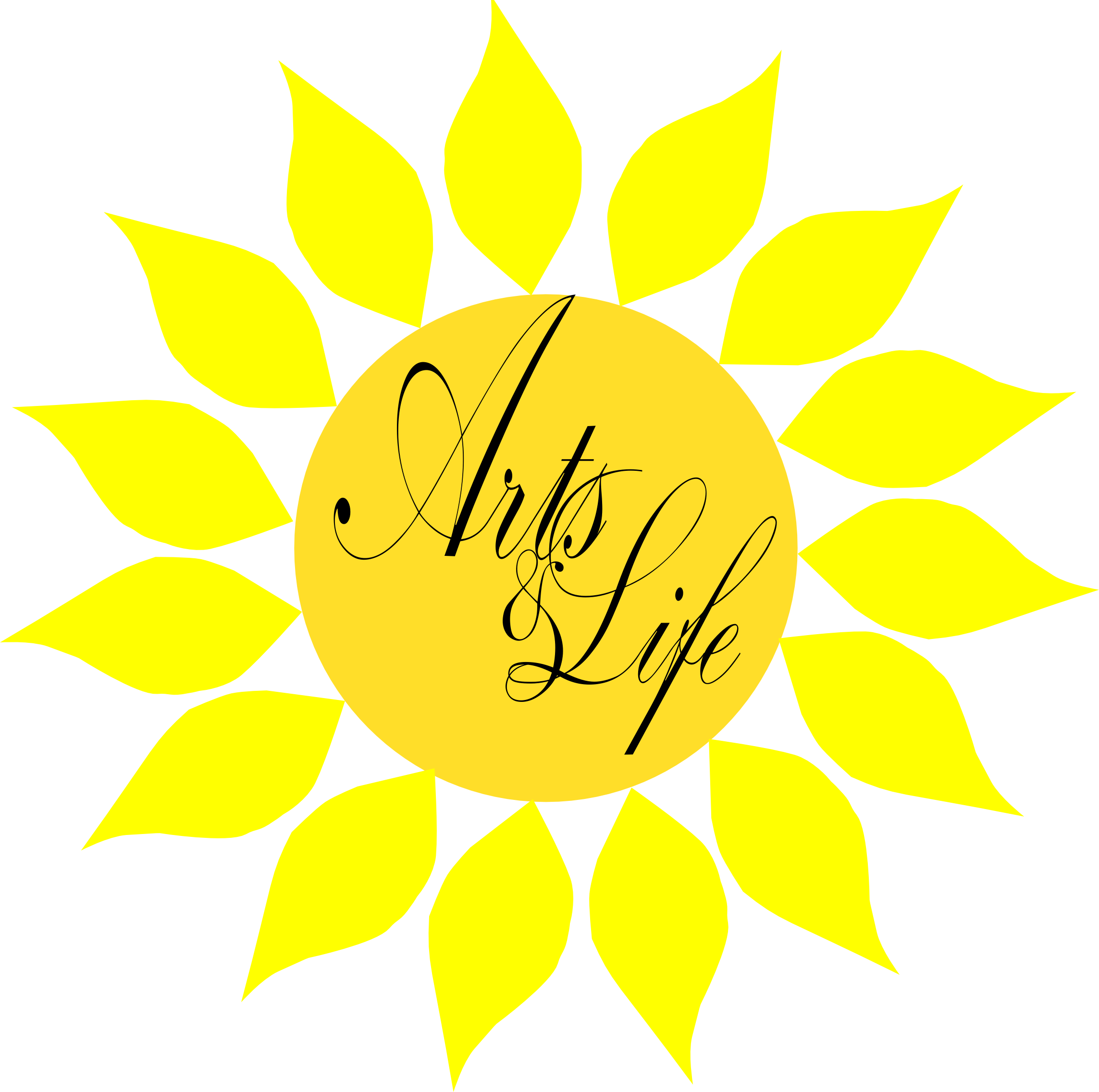

Leave a comment