Jari-jarinya yang sudah kelihatan segar menghitung. “Masih enam kali lagi,” gumamnya sambil duduk di beranda rumahnya di lereng Gunung Merapi menjelang maghrib. Mata kanannya masih tertutup perban putih. Rapi tersembunyi di balik kacamata yang dipakainya. Mata kirinya terbersit sinar kehidupan yang menyiratkan semangat yang masih tersisa. Jambangnya yang dulu memenuhi wajah di bagian kanan dan kirinya kini meninggalkan permukaan kulit yang kelihatan kuning bersih. Janggutnya yang dulu lebat pun tinggal menyisakan beberapa helai rambut putih yang masih menggantung di dagunya. Wajahnya yang dulu garang dan selalu identik dengan stigma keras kini makin melembut menyiratkan keramahan. Seolah kegarangan itu tanggal helai demi helai seiring kesembuhan yang direngkuhnya.
Pak Haji, panggilanku untuk adik ibuku, kini menampilkan sosok lain. Kelembutan, keramahan yang sempat terenggut selama beberapa tahun kini hinggap kembali di raut mukanya. Aku teringat ketika dulu beliau mengajakku diskusi soal keyakinan yang berbeda. Dia bersikukuh dan memaksa sambil menghakimi bahwa keyakinanku sebagai orang Katolik adalah salah belaka. Penghakimannya menggiring agar aku balik badan dan mengikuti keyakinan yang dianutnya. Perdebatan sore itu berakhir ketika aku hanya mengatakan tentang falsafah rel kereta api. “Biarkan dua rel itu selalu berada pada kedua sisinya. Biarkan ada bantalan yang mempertautkan kedua lajur rel. Karena dengan lajur rel demikian maka kereta tidak akan terguling,” kataku. Beliau diam dan pergi sambil bersungut-sungut.
Kini di usianya yang makin senja tidak ada lagi sesi diskusi tentang keyakinan. Kepalanya yang licin ditinggalkan rambut itu justru memperlihatkan kematangan. Wajahnya yang dulu terkungkung kelebatan cambang dan janggut tebal kini makin terkuak dengan roman kebapakan dan keramahan. Dua kali obat kemoterapi yang menyusuk ke setiap jalur pembuluh darahnya seolah menyuntikkan kehidupan baru. Kanker di mata dan hidungnya seolah sudah tak kerasan lagi tinggal di tubuh Pak Haji. Senyum kemenangan dalam kepasrahan itu terasa membekas, memberikan kehangatan saat malam dingin di lereng pegunungan di rumahnya. ***
Sebuah cerpen tiga paragraf (pentigraf) karya Leo Wahyudi S
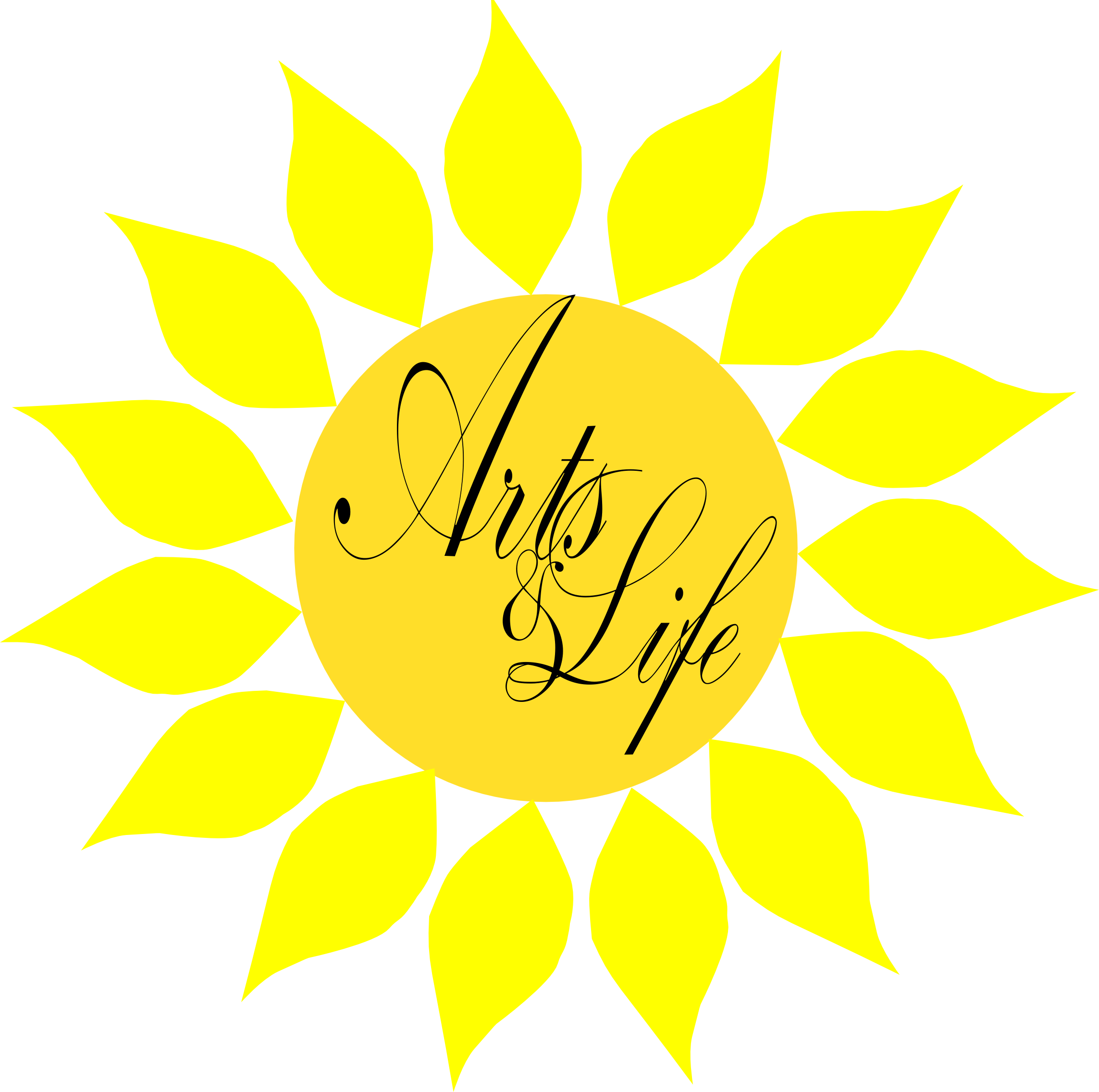

Leave a comment