Lalu lalang kendaraan tak ada putusnya. Semua berjalan seolah ingin mengalahkan sang waktu. Berebut dan ngebut demi sampai di rumah lebih cepat. Tapi hiruk pikuk lalu lintas di Jakarta itu tak mengusik pembicaraan Jefa dan Yuda yang menyusuri jalur trotoar menuju stasiun kereta. “Jadi saya sudah hampir enam bulan ini tidak pernah bertegur sapa dengan istri di rumah. Saya kesal. Saya tiap malam juga tidur dengan anak saya. Bahkan kalaupun bisa, saya ingin waktu berjalan panjang sehingga saya tak perlu pulang ke rumah. Bosan saya di rumah. Bawaannya curiga melulu. Sebal rasanya melihat istri saya. Saya kerja untuk keluarga. Mobil saya tinggal biar dipakai untuk bekerja dan mengantar anak sekolah. Tapi ketika melihat jarak di speedometer, rasanya tak masuk akal dengan pemakaian wajar. Uang belanja juga selalu kurang. Pusing saya, Mas. Kalau saja saya belum punya anak, sudah saya tinggal istri saya, Mas,” kata Jefa kencang berusaha mengalahkan riuhnya kendaraan orang sore itu.
Dugaan Jefa makin mengerucut dari hari ke hari. Ia melihat tagihan-tagihan yang melambung, uang belanja yang tak pernah cukup. Istri jarang di rumah. Hatinya menggelegak saat pikirannya tergiring pada bayangan akan perselingkuhan. Jefa tinggal menunggu penghakiman terakhir sebelum membuat keputusan final untuk bahtera rumah tangganya. Dia juga lebih sering pergi ke luar kota untuk perjalanan dinas. “Pernahkan dalam hidupmu berselingkuh atau bermain api dengan wanita lain? Saya tak ingin menyelidik kehidupan pribadimu. Tapi pernahkah terlintas bahwa apa yang dilakukan istrimu adalah satu bentuk pembalasan atas ketidaksetiaan yang pernah ia alami?” tanya Yuda. Jefa menoleh ke muka Yuda dengan mata agak membelalak yang kemudian perlahan meredup lalu menunduk, menatap garis-garis trotoar yang saling sambung.
Tak perlu kata-kata gamblang, sikap Jefa sudah memberikan jawaban yang jujur. Yuda mafhum, tanpa sedikitpun ingin menghakimi. Keduanya terdiam. Membiarkan suara knalpot kendaraan meraung-raung berebut jalan. “Ya kalau ini wujud pembalasan saya jadi bingung. Yang saya tidak suka adalah ketidakjujuran istri saya, Mas. Saya harus bagaimana?” ia mengelak sambil menempelak. Yuda tersenyum dan berkata, “Surga dan neraka itu berada di rumah kita. Obat dari penyakit tak pernah jauh dari rumah kita,” kata Yuda pendek. Jefa kembali menunduk. Kepalanya mendadak terangkat penuh semangat ketika bel kereta komuter sudah memanggilnya agar bergegas masuk ke gerbong. “Saya pulang dulu ya, Mas Yuda!” katanya sesaat sebelum pintu kereta menutup.***
Sebuah cerpen tiga paragraf (pentigraf) karya Leo Wahyudi S
Tulisan telah dimuat di buku antologi “Surga untuk Pohon Ulin dan Cerita-Cerita Lainnya”, Sidoarjo: Penerbit Delima, (2018).
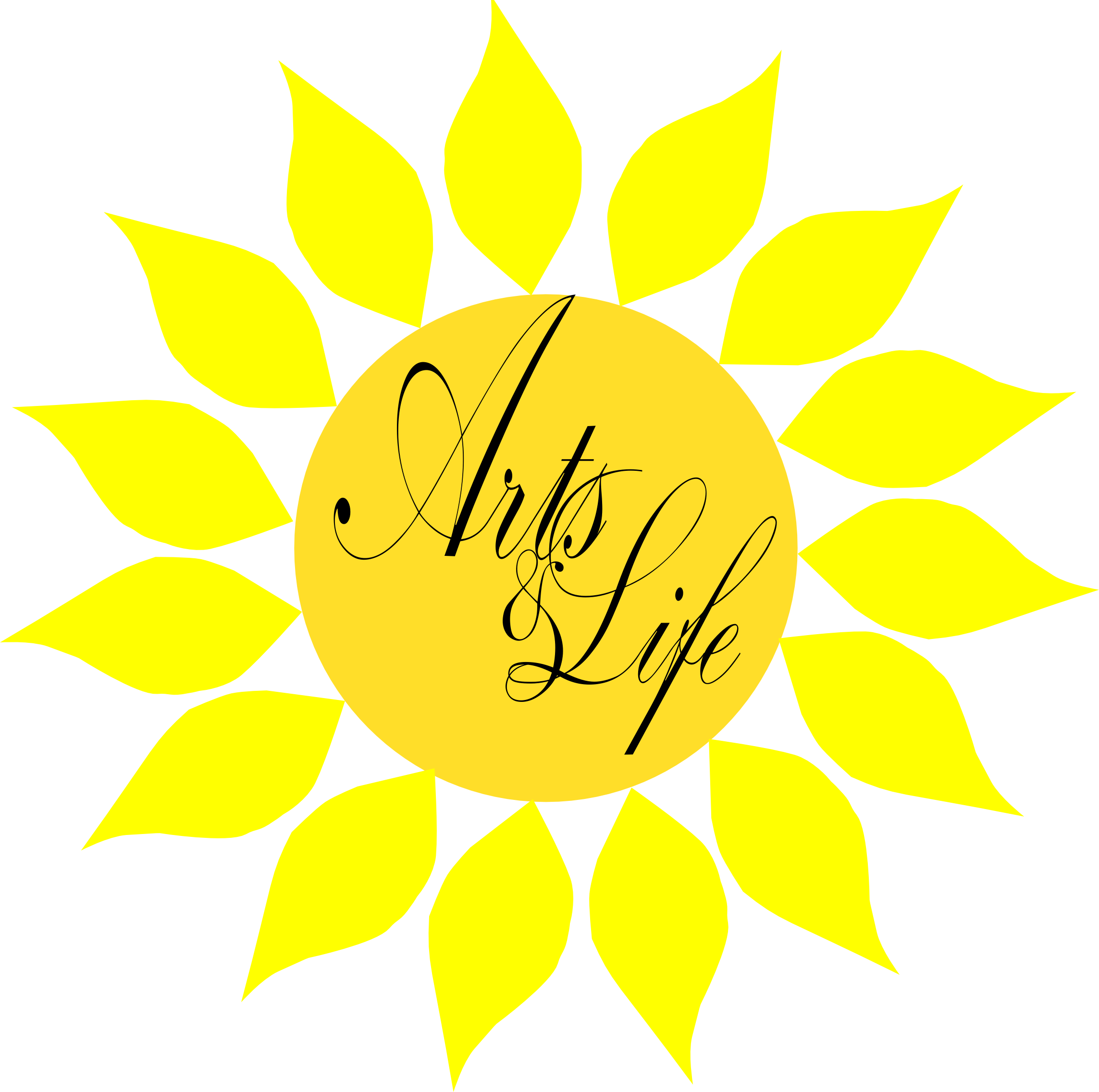

Leave a comment