Liburan panjang akhir pekan bulan Juni ini tidak bakal kusia-siakan. Aku sudah punya niat untuk me time. Ada waktunya untuk memanjakan diriku sendiri setelah bertahun-tahun hidup diperbudak dengan segala tetek bengek kewajiban. Mulai dari kewajiban sebagai anak perempuan sulung, anak sekolah, anak kuliah, anak magang, anak kos, hingga kini anak kantoran. Bukannya tidak bersyukur, cuma perbudakan kewajiban itu membuatku sampai lupa untuk menyapa tubuhku yang kini sudah mulai merangkak setelah hidup 22 tahun.
Aku kini sudah sampai pada impian yang dulu bahkan tak berani kuangankan. Aku ternyata bekerja di sebuah pabrik di Kawasan industri di timur Bekasi. Aku jadi orang kantoran. Rasanya aku makin hari makin mencintai pekerjaanku. Buktinya, energi cintaku itu seolah menebar. Bukan tebar pesona, tapi tebar cinta yang membuat vibes positif di sudut mana pun di kantorku. “Chandra mah, bikin semua orang hepi di sini,” kata salah seorang karyawati senior yang lumayan dekat denganku suatu hari. Aku tidak mau ge-er, tapi banyak yang bersaksi demikian. Aku seolah menemukan duniaku, dunia persahabatan, persaudaraan yang tulus, tanpa sekat. Memang aku sendiri merasa santai saja berhubungan dari level direktur sampai office boydi kantorku. Bagiku itu bukan hal aneh, tapi menyenangkan. Tak ada tendensi untuk menjilat sana sini biar dapat perhatian. Semua tulus. Itu saja yang kurasakan.
Aku tidak mau pulang kampung bersama keluargaku di Jawa Tengah. Akhir pekan yang panjang itu ingin kugunakan untuk menghibur diri di tengah kepenatan industri dan beban pekerjaan. Kupilih Puncak Sempur di Karawang. Aku belum pernah ke sana dan aku sekaligus ingin membuktikan sendiri dari anggapan bahwa Karawang selama ini dikenal jauh dari pusat metropolitan, panas, banyak industri, dan segala label yang kurang mengenakkan.
Ternyata benar. Aku bisa menemukan keindahan alam yang luar biasa di Puncak Sempur. Tak kalah dengan Puncak yang selama ini jadi destinasi wisata orang Jakarta. Yang kulihat hanya keindahan dan kesejukan alami. Rasanya kepenatanku perlahan mulai menghilang. Aku bahagia. Sebuah kata yang kurindukan bertahun-tahun dalam hidupku. Aku tak pernah merasakan sebahagia ini dengan diriku. “Terima kasih, Tuhan, aku bahagia dengan keindahan ini,” bisikku sebelum aku melangkah pulang.
***
Tiga hari setelah aku healing di Puncak Sempur, semua kehidupan berjalan normal. Pekerjaan seperti biasa, bisa kulakukan dengan baik. Hanya aku merasa sedikit aneh dengan tubuhku. Mulai kurasakan penyakit lamaku menggeliat, merangkak sebelum akhirnya menyerangku dari dalam. Ya, asam lambungku sepertinya kambuh. Kupikir hanya kecapekan fisik saja. Di kantor aku masih bisa tertawa-tiwi ke sana ke mari dengan kolega. Tapi, perlahan tapi pasti, fisikku mulai memberontak. Ada rasa panas yang menjalar dari perutku.
Sepulang kantor, kurebahkan tubuhku di kasur ala-ala anak kos. Alih-alih mengurangi rasa nyeri yang mulai menjalar ke mana-mana, aku mencoba berbaring diam. Belum sempat kumakan nasi dan lauk kesukaanku yang kubeli sepulang dari kantor tadi sore. Kupegang ponselku, sahabatku yang selalu setia menemaniku di kala duka dan duka. Bukannya tak ada suka, tapi rasa suka itu setelah aku membuka ponsel, menonton TikTok, YouTube, atau sekedar berkirim pesan. Justru dukaku kularikan pada sahabatku itu, ponsel pintar yang selalu mengerti aku.
Waktu pun merangkak meninggalkan angka kecilnya. Hari mulai malam. Suasana kosku makin hening. Justru dalam keheningan itu, kurasakan tubuhku makin sakit, makin melemah. Seolah nyeri di perutku tak kunjung pergi. Tubuhku pun memanas. Kemarin sudah kurasakan tanda-tanda demam itu, tapi kutepis segala pikiran negatif. Aku mau flu, begitu pikirku. Tapi malam ini yang kurasakan bukan demam flu biasa. Makin lama makin menggigil. Nafasku pun makin malam makin memendek.
Di batas kesadaranku, kuraih ponselku. Kucari nama-nama teman dan kolega kantorku, mulai dari manajer sampai teman dekat. Tak lupa, aku pun menelepon bapak kos. Pesanku ke semua orang itu satu, aku dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, tolong urusin diriku, apa pun kondisinya.
“Pak, kamar tidak saya kunci ya. Kalau ada apa-apa tolong hubungi keluarga saya ya, Pak,” kataku di sisa-sisa kesadaran pada bapak kos yang kelihatan panik di ujung kamarku malam itu.
Entahlah, aku hanya merasa mungkin inilah saatku untuk pergi. Aku tidak lebay. Aku hanya ingin memanfaatkan sisa kesadaranku untuk mengabarkan kondisiku malam itu. Badanku makin panas. Nafasku mulai tersengal. Dadaku mulai sesak. Mataku nanar. Lemah, tak mampu kugerakkan tubuhku lagi. Aku hanya terbaring pasrah. Untuk terakhir kalinya, pikirku, aku masih mengirim pesan pada salah satu manajer yang terlupa. Kulihat jam digital di ponselku. Pukul 23.58.
Di tengah nafasku yang mulai satu satu, kutatap langit-langit kamar dengan sisa kelopak mata yang membuka. Antara sadar dan tidak, kutonton sebuah film kehidupanku. Aku seolah berada di gedung bioskop Twenty One untuk menonton seluruh perjalanan hidupku dari kecil.
Kugambarkan film itu seperti film drama keluarga. Orang tuaku adalah aktor utamanya. Diriku ternyata juga menjadi pelakon di kisah itu. Mamaku jadi aktris antagonis, seperti seorang ibu tiri dalam kisah anak-anak di jaman aku kecil. Papaku menjadi tokoh tidak jelas. Begitu pun adikku. Aku sendiri menjadi tokoh protagonis atau korban atau yang dikorbankan. Pikiranku capek. Kesadaranku mulai turun. Aku hanya menonton adegan demi adegan.
“Makanya kamu itu jangan sakit. Bikin repot. Bikin susah orang tuamu, tahu!” kata mamaku yang selalu menjadi litani wajib di saat aku sakit.
Dua kata itu menghunjam dalam hatiku, meninggalkan luka menganga yang tak pernah sembuh. Darah sakit hati itu terus mengucur. Aku lebih suka dimaki dengan binatang daripada kata “menyusahkan”, “merepotkan”. Dua kata itu membuat hidupku hancur. Seolah tak ada gunanya aku dilahirkan.
Banyak sekali adegan mamaku sedang mengumbar kemarahan. Papaku hanya diam sambil merokok. Aku pun ikut diam, memendam dendam pada mamaku. Ibu yang melahirkan aku. Aku benci dengan ibuku. Aku kecewa dengan papaku yang tak pernah membelaku di depan mama. Aku jadi anak yang tak berharga di tengah mamaku yang keras kepala, menang sendiri, egois, dan papaku yang lemah dan pengecut itu.
Di adegan selanjutnya kulihat diriku yang menangis. Aku kehilangan banyak teman sejak aku di SMP sampai SMA. Aku bisa bergaul dengan siapa pun. Tapi tak ada yang mau jadi sahabat yang dekat dan mengerti aku. Teman-temanku satu demi satu pergi meninggalkanku. Alasannya karena aku anak mami yang terlalu dilindungi orang tuaku. Aku malu. Aku sedih. Aku luka. Tapi tak ada orang yang mau kuajak bicara untuk membagi lukaku untuk melunturkan kebencianku pada mamaku dan kekecewaanku pada papaku.
Sejak itu makin mengurung diri. Aku mulai bersahabat dengan diriku sendiri. Aku mulai akrab dengan kebencianku dengan mama. Aku mulai menikmati dendam itu. Kamarku adalah istanaku yang indah karena di sana aku bisa bicara dengan diriku, berkeluh kesah dengan diriku.
Kalau pun aku badung, Bengal, dan sempat jadi gadis nakal, aku mengakui semua itu. Kalau aku gampang suka laki-laki brengsek dan tidak jelas statusnya, kulakukan semua itu dengan sadar. Kalau aku ingin minggat bersama laki-laki yang asal tubruk di jalanan, itu pun dengan kesadaranku. Kesadaran bahwa aku benci dengan mamaku dan kecewa dengan papaku yang egois, yang selalu mencampakkan aku dengan kata-kata kasar. Saat adikku lahir, perhatian itu sudah pindah semua. Aku bukan siapa-siapa lagi. Seolah mamaku menyesal melahirkan aku sebagai anak sulung. Aku pun merasa hidupku makin sia-sia. Tanpa pernah ada pembelaan dari papaku yang seharusnya bisa. Tapi papaku pengecut. Kalah dengan keegoisan mamaku. Aku menjadi semakin liar dan jalang dengan tiap laki-laki karena aku ingin membalaskan sakit hatiku. Biar orang tuaku sakit hati, malu melihat kelakuanku. Sengaja kulakukan ini berulang kali agar mereka tahu bahwa aku tetap merepotkan dan menyusahkan.
Bahkan sempat pula kutonton adegan di mana aku tidak bisa tidur di suatu malam. Aku yang sudah menjadi gadis remaja itu tak pernah mendapatkan pendidikan seks dari orang tuaku yang kolot, yang selalu tabu membicarakan hal itu. Aku harus mencari jawabnya sendiri. Bahkan seperti malam itu, aku harus menafsir sendiri suara-suara nafas yang terengah di kamar sebelahku. Aku bukan bocah kecil yang polos. Aku sudah tahu sendiri apa yang kira-kira terjadi di bilik sebelah. Suara-suara itu membuatku jengah, jijik, berontak, marah, protes. Aku seolah ingin berteriak dan lari dari rumah. Celakanya, kupingku harus menafsir suara desah orang tuaku itu berpuluh-puluh kali. Dan berpuluh-puluh kali pula kemarahan dan jiwa pemberontakanku keluar. Aku sewot. Kudiamkan orang tuaku seharian tanpa bertegur sapa demi meluapkan kemarahanku. Aku tidak benci pada kegiatan mereka sebagai suami istri. Aku hanya ingin mereka melakukannya ketika aku dan adikku sudah terlelap, biar kupingku dan imajinasiku turut menafsirkan hubungan suami istri itu dalam benakku.
Untunglah aku menemukan sahabat baru. Sebuah pisau dapur yang selalu menemaniku dalam kesakitan dan keputusasaanku. Dalam kegelapan dan kegalauanku pisau sahabatku itu selalu menghiburku. Apalagi saat kugores nadiku. Saat darah mengucur perlahan, aku tersenyum puas. Aku seolah sedang menyambut dunia baru yang lebih indah daripada keluargaku. Bekas-bekas luka goresan di nadiku sampai sekarang menjadi saksi kunci dan saksi bisu yang bisa berkisah di tengah keputusasaanku. Tak pernah ada yang tahu tentang kisah ini. Hanya pisau sahabatku dan nadiku yang mengerti perasaanku. Semua kulihat nyata di adegan film yang sedang kutonton dalam sakratul mautku.
Kunikmati adegan demi adegan malam itu. Tanpa ada rasa. Rasa benci, kecewa, marah, dendam, sakit hati, nyeri, semua sirna. Yang kurasakan malam itu hanyalah nafas yang makin tersengal karena dadaku makin sesak. Tak kutemukan pula sebulir air mata yang menetes di kedua mataku. Wajahku kering. Hatiku kering. Hanya kesadaran dan mataku yang masih tersisa untuk melihat kembali seluruh kisah hidupku. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.59 di malam itu. Malam sakratul maut. Mataku hampir menutup, seiring nafas terakhir yang kuhirup dengan susah payah.
***
Film drama kehidupanku sudah selesai. Badanku makin menggigil, tapi tak kurasa lagi. Mataku sudah setengah menutup, menunggu tarikan nafasku yang terasa makin berat. Aku sudah hampir tak merasakan apa pun. Aku sudah pasrah. Tak ada pilihan mau mati atau hidup. Hanya pasrah.
Tiba-tiba, entah kekuatan dari mana, aku berucap, “Aku pasrah. Aku mengampuni mamaku saat ini. Tuhan, ampuni mamaku!” Aku masih ingat dan tidak tahu mengapa aku mengucapkan kalimat itu. Bahkan kusebut nama lengkap mamaku tiga kali. Aku sudah pasrah dan siap, entah hidup atau menuju alam kematian.
Aku terdiam. Mataku terpejam. Nafasku masih sesak. Setiap tarikan nafasku seolah aku sedang berada di ambang sakratul maut, entah hidup, entah mati. Satu, dua, tiga, empat, lima … kuhirup dan kuhembuskan nafas penghabisan. Seingatku, waktu menunjuk pukul 24.00. Yang kurasa hanya sakit fisik di perutku. Tapi beban hatiku terasa ringan. Jiwaku seperti terlahir kembali.
***
Aku tidak peduli kata dokter. Dibilang tipus, disuruh opname, disuruh minum antibiotik, aku tidak peduli. Badanku memang sakit. Lemas sekali rasanya. Yang jelas, aku menemukan rasa yang tak pernah kualami selama hidupku. Rasa plong, rasa ringan, rasa bahagia, yang tak bisa kulukis dengan kata-kata.
Lucunya, aku baru menemukan salah satu makna kata inner beauty, kecantikan dari dalam diri. Ternyata, getaran perasaanku yang baru, yang bahagia itu makin memancar dan menular di sekelilingku, di kantor, dan bahkan di keluarga.
“Pakdhe, sekarang mamaku beda. Tumben banget. Aku sudah mulai bisa bercanda, bisa ngobrol santai dengan mama. Kayaknya dia mulai berubah. Kenapa ya, Pakdhe?” kataku suatu hari dengan Pakdhe Wawan, orang yang selama ini mau mengerti curahan hatiku dan segala persoalan hidupku.
“Wah, Pakdhe ikut seneng, Chandra. Kamu sendiri sudah menemukan kata pasrah dan memaafkan. Kayaknya, bukan mamamu yang berubah, tapi kamu yang kini sudah berubah,” sahut Pakdhe.
“Masak sih?”
“Pakdhe yakin. Sampai kapan pun, kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa berubah adalah diri kita sendiri. Rupanya kamu sekarang sudah berubah ya?”
Dalam hati aku akhirnya mengiyakan. Apakah ini dampak dari sakratul mautku kemarin? Apakah ini karena aku sudah bisa memaafkan mamaku? Tapi, yang jelas, aku sudah bisa merasakan dan mengalami rasa bahagia dengan diriku. Dunia terasa indah. Keluargaku bukan ancaman lagi. Aku sudah punya hidup baru.
Hanya diriku sendiri yang bisa menyembuhkan semua luka batinku. Aku memegang kata-kata Pakdhe suatu kali yang menyuruhku untuk berdamai dengan diri sendiri agar bisa membangun benteng kuat bagi kebahagiaanku sendiri. Karena segala masalah, sakit hati, kekecewaan itu muncul karena kita bereaksi dan berekspektasi terhadap dunia, orang lain, yang ada di sekitar kita. Kita membiarkan dunia luar mendikte perasaan kita. Jutaan kata doa, ribuan litani, ribuan untai rosario, tak juga kuat menghapus sakit hati dan kebencianku kalau bukan aku sendiri. Itu yang kutemukan.
“Pesan Pakdhe, pertahankan kesadaranmu itu. Hidup selalu berproses. Hanya kesadaranmu yang akan tetap membuat hidupmu damai dan bahagia,” kata Pakdhe.
Aku tersenyum bahagia. Aku makin mencintai hidupku, karena ternyata hidupku masih memberi arti bagi teman-temanku. Pakdhe memelukku dengan hangat untuk menyambut diriku, seorang Chandra yang baru. Chandra yang bahagia. ***
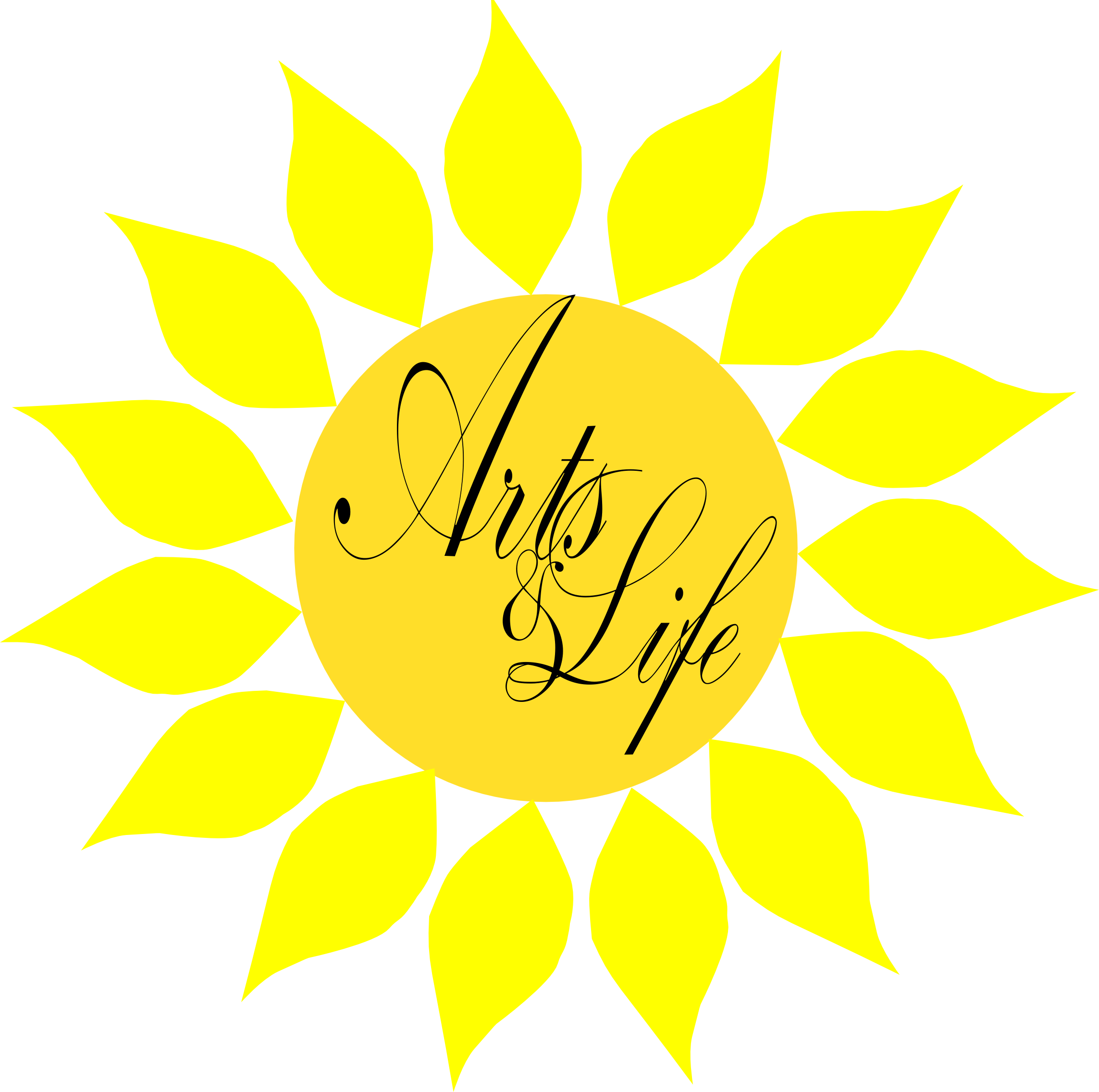

Leave a comment