Judul ini kesannya memang provokatif. Apalagi bagi orang yang belajar Teologi Harapan, pasti sebelum membaca sudah pasang kuda-kuda. Tapi tenang, saya tidak sedang membahas teologi. Saya ingin ngobrol soal kehidupan sehari-hari ketika kita disetir oleh harapan-harapan, berharap-harap, yang semuanya semu.
Aku berharap anakku bisa lolos ujian di sekolah terbaik itu, tapi ternyata gagal.
Aku berharap pasanganku itu tahu apa sebenarnya yang aku harapkan dan inginkan.
Aku berharap bosku itu tidak culas, tidak egois, tidak menang sendiri, sok kuasa, tapi ternyata aku malah tidak digubris.
Aku berharap orang itu baik, ternyata egois dan pelit sekali.
Aku berharap dia tahu kalau aku itu suka sekali sama dia, senyumnya, tampangnya.
Harapanku sih anakku itu tahu etika dalam pergaulan, tapi dia jadi jalang begitu.
Aku berharap seharusnya dia tahu bagaimana bersikap yang baik ketika di rumah, tapi yang ada malah selalu bikin kesal.
Aku berharap banget mbok Tuhan bisa ngertiin kondisiku sekarang, tapi malah dibiarkan makin terpuruk.
Aku kecewa dan sakit hati, karena harapanku kandas di tengah jalan.
Ada segudang harapan yang sering kita lontarkan atau ucapkan dalam hati agar orang lain, situasi di luar kita itu bisa berubah seturut keinginan kita. Tapi ketika harapan itu tak kunjung menemukan realitas seperti yang kita dambakan, ujung-ujungnya kita hanya akan didera rasa kecewa, sakit hati, jengkel, marah. Tanpa sadar kadang hidup kita didikte oleh harapan dan keinginan-keinginan untuk mengubah dunia atau orang di sekitar kita. Akhirnya kita stres dan marah-marah sendiri.
Sayangnya, hidup itu tidak harus semulus seperti harapan kita. Toh, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan selalu datar dan tak berkelok, air tenang tak bergelombang, hati tak selembut sutera, hujan tak pernah reda. Hidup itu selau ada dualisme, bersih dan kotor, berhasil dan gagal, salah dan benar, gelap dan terang, baik dan buruk. Lalu, bagaimana kita menghadapi dunia semacam ini?
Seorang guru spiritual India, Sri Chinmoy, mengatakan, kedamaian itu akan tercipta ketika kita berhenti berharap-harap. Minimal, semakin kita menurunkan ekspektasi atau harapan, semakin damai hidup kita. Saya sendiri mengalami. Saya sadar dalam artian tertentu saya perfeksionis. Tapi itu malah membuat stres. Maka saya belajar untuk menurunkan, dan perlahan menghilangkan harapan dan ekspektasi yang tidak perlu. Saya belajar menerima ketidaksempurnaan sebagai kesempurnaan. Karena toh tak ada yang sempurna, sehingga orang berlomba mengejar kesempurnaan.
Tidak ada orang yang mau mengalami penderitaan hidup. Tapi kadang orang menciptakan sendiri penderitaannya, salah satunya karena pikirannya dipenuhi harapan-harapan tadi. Agar bisa mengalami hidup yang damai, jangan kita biarkan hati dan pikiran didikte oleh harapan, ekspektasi. Caranya adalah dengan menerima apa yang ada di luar diri kita apa adanya. Tanpa protes, tanpa berharap, tanpa syarat, tanpa “tapi” dan tanpa menghakimi.
Dunia di luar kita ada bukan untuk selalu memenuhi keinginan kita. Semakin besar harapan dan ekspektasi kita, semakin bagus kita mempersiapkan hati untuk kecewa. Maka, kalau ingin hati dan pikiran damai, berhentilah berharap-harap, menilai, dan mengharuskan keadaan atau orang agar seturut kemauan kita. Hidup itu menerima apa yang tidak kita inginkan, dan membiarkan pergi apa yang kita harapkan, kata guru ngaji Syaiful Karim. Menerima kenyataan apa adanya, tanpa syarat. Inilah biang kedamaian. Bukan berharap-harap, karena ini akan menjadi biang penderitaan dan kekecewaan.***(Leo Wahyudi S)
Foto dari https://www.istockphoto.com/id/search/2/image?phrase=expectations+reality
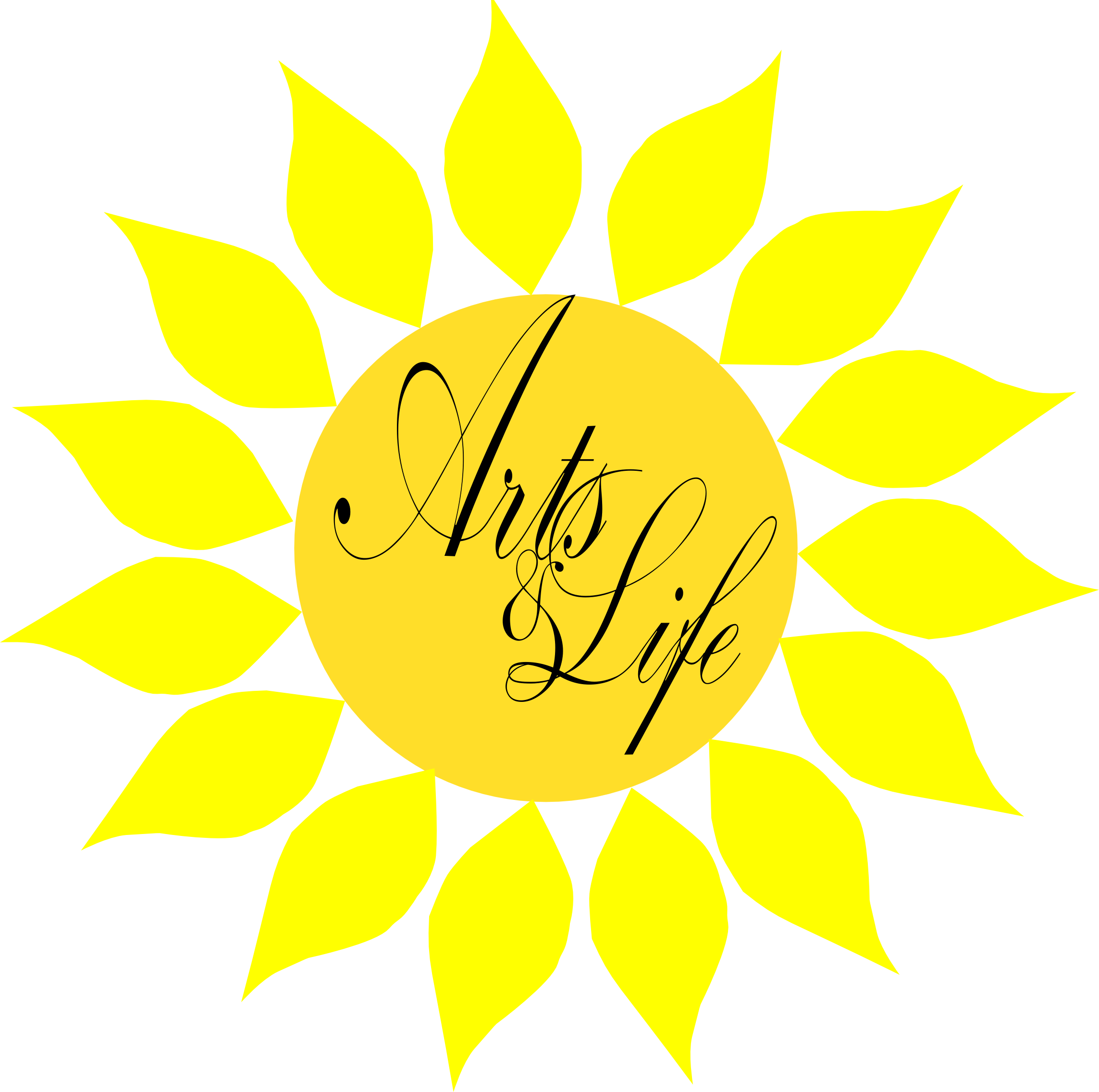

Leave a comment