Tulisan ini tidak untuk membuat kuatir para orang tua yang telah memiliki anak-anak remaja. Saya hanya berkisah dari obrolan dengan anak perempuan saya.
Suatu ketika, saya terkejut. Anak saya tiba-tiba curhat. Ia menceritakan situasi sekolahnya dan teman-temannya yang berasal dari latar belakang beragam. Yang cukup mengejutkan adalah kenyataan bahwa dia ada yang naksir, jatuh hati. Yang lebih mengejutkan, yang suka dan berani mengungkapkan adalah temannya perempuan. Anak saya sempat shock.
Saya pun tak kalah shock. Terkejut sekali dengan fakta modern di sekolah negeri yang notabene, antara lain, punya stigma agamis, tapi sudah ada remaja dengan orientasi seksual yang menyimpang yang berani terbuka. Tapi ini fakta. Bahwa anak-anak remaja sekarang sudah makin terbuka mengungkapkan perasaan dan kejujurannya.
Saya pun akhirnya memberanikan diri terbuka pula ke anak saya untuk menanyakan hal yang pribadi. Saya tanyakan dengan hati-hati apakah dia punya orientasi seksual normal atau yang beda. Dan, puji Tuhan, alhamdulillah, anak saya menjawab dengan lantang, “Aku normal, ayah.”
Dengan kasus ini pula, saya lalu menanyakan ke anak-anak laki-laki saya. Semuanya negatif, alias normal. Tapi anak bungsu saya sempat di-bully di sekolahnya. Beredar desas-desus bahwa anak saya dianggap hombreng (homo), karena, kata teman-teman dan gurunya, anak saya ganteng, putih, gagah, getol fitness, tapi belum punya gebetan atau pacar. Saya tanya kenapa dia tidak punya pacar. “Ya karena aku belum pengen aja, ayah. Aku anggap semuanya teman. Tapi kalau rasa suka sih, adalah,” jawaban anak saya serasa oase di gurun pasir.
Saya tidak mau mendiskriminasikan orang dengan orientasi seksual berbeda. Karena penasaran saya lalu berkonsultasi dengan seorang teman yang LGBTQ bagaimana menghadapi situasi seperti anak saya. Ia dengan senang hati menceritakan dan memberikan banyak tips pada saya sebagai orang tua dalam mendidik anak. Ia cukup fair dan bahkan memberikan tips agar anak tidak masuk dalam pergaulan di luar orientasi normal itu.
Saya mendapat pelajaran dari peristiwa ini. Bahwa isu LGBTQ itu sudah merebak ke semua lini kehidupan remaja, bahkan sampai sekolah negeri atau swasta. Hal ini pun diamini oleh keponakan-keponakan saya yang lain. Mereka tertawa dengan keterkejutan saya. “Itu biasa, Om. Kami sering mengalami begitu. Banyak teman-teman kita begitu,” katanya enteng.
Belum lama juga, seorang sahabat curhat ke saya untuk hal yang kurang lebih sama. Anak perempuannya yang masih SMP tiba-tiba ingin pindah sekolah. Ia mengalami perundungan yang kurang lebih sama oleh teman sejenisnya. Anaknya mengalami tekanan mental yang luar biasa yang membuatnya ingin pindah. Sekolah pun seolah kurang peduli.
Saya mencoba menerima kenyataan itu sebagai fakta. Saya tidak berhak untuk mengubahnya kecuali berdamai dengan keadaan itu. Saya hanya menyikapi dengan pikiran yang lebih terbuka. Berbicara soal pendidikan seksual, orientasi seksual, pergaulan jangan lagi dianggap tabu. Bahkan dalam artian tertentu kita harus berani berkompromi dengan etika dan moralitas yang kian terdegradasi dewasa ini. Kita tak perlu melawan dengan agresif arus jaman itu.
Yang menyelamatkan adalah kewarasan dan prinsip hidup yang kuat. Itu saja yang saya tekankan pada anak-anak. Prinsip itulah yang harus dibuktikan agar terlihat jelas oleh orang lain. Ibarat berdiri kokoh di tengah arus deras sungai keruh. Cukuplah bisa berdiri tegak tanpa terbawa arus. Tidak usah berusaha melawan atau mengeringkan air sungai itu. Syukurlah kalau bisa berpijak di batu-batu keras agar bisa menyeberang ke aliran yang lebih bening dan tidak berarus deras.
“Emang banyak anak sakit mental sekarang. Ngeri. Kita sendiri harus berani melawan dengan sikap kita,” kata anak perempuan saya.
Harian Kompas pada 10 Juli lalu menurunkan tulisan tentang krisis kesehatan mental pada Generasi Z di Indonesia. Dituliskan bahwa menurut survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 menemukan sekitar 5,5 persen remaja usia 10-17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental yang biasa disebut orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sekitar 34,9 persen memiliki satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Jika ditotal jumlah remaja berusia 10-19 tahun ada 46,2 juta jiwa, maka ada sekitar 16,1 juta remaja tergolong OMDK.
Fakta ini cukup membuktikan reaksi anak saya tadi, sakit mental. Tugas kitalah sebagai orang tua untuk selalu membuka jalur komunikasi yang dialogis dua arah dengan anak. Hanya lewat komunikasi personal yang menurut saya masih bisa menjadi gawang, selain pendidikan nilai-nilai moral, etika, dan agama. Sudah bukan jamannya lagi kita bertindak sebagai orang tua yang maha benar, maha berkuasa, maha tahu, maha mendikte. Orang tua harus mulai mau belajar berkompromi, berjiwa sportif, dan bahkan mau belajar dari anak-anak kita. Salam waras, salam sehat untuk kita dan anak-anak kita.***(Leo Wahyudi S)
Foto dari https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/youth-mental-health-day-2023/
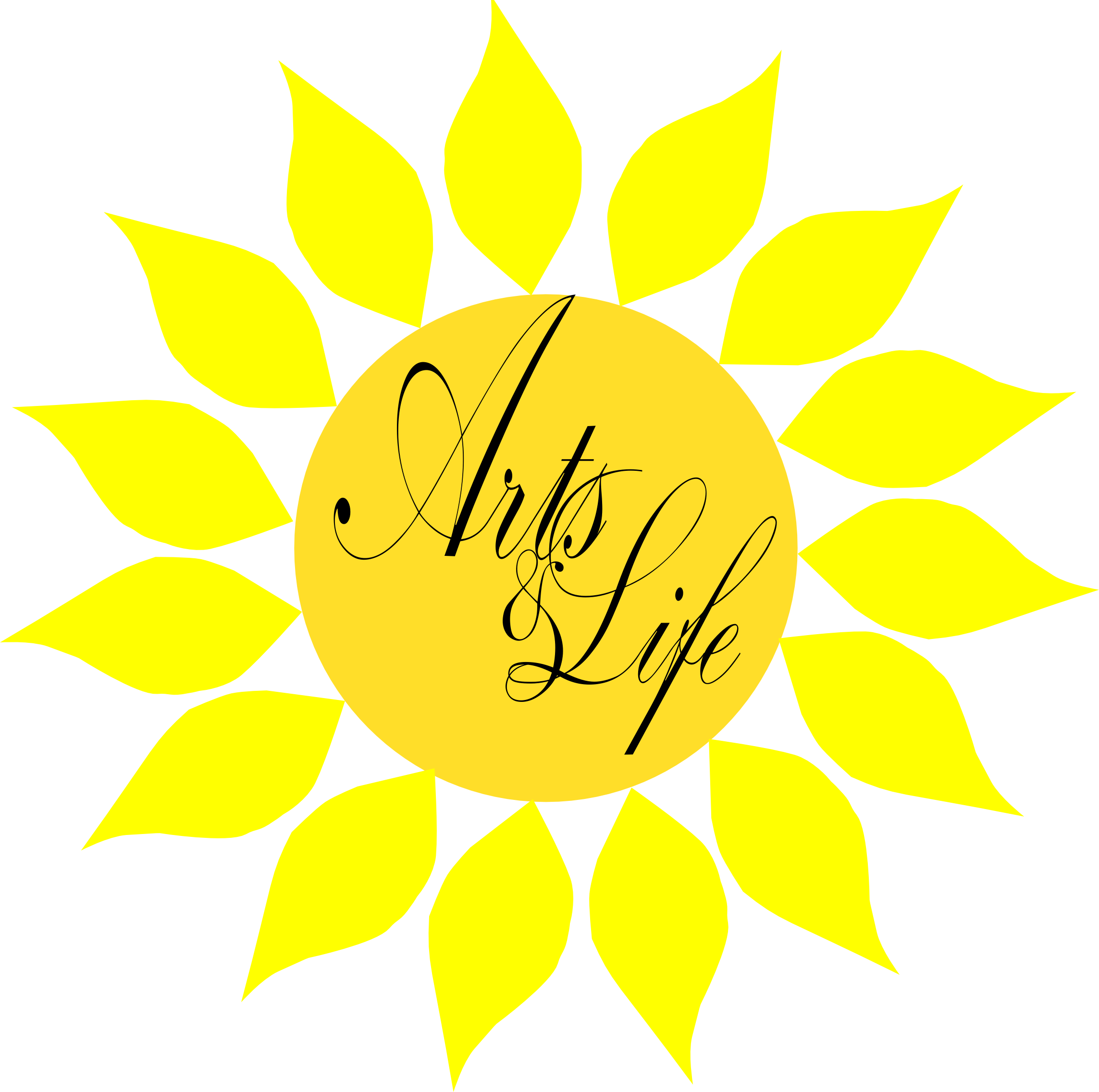

Leave a comment