Benarkah Agama Bisa Menjadi Mesin Pembunuh Paling Ampuh?
Judul ini saya tampilkan bukan untuk sebuah provokasi di tengah isu intoleransi di Sukabumi yang baru terjadi. Ini terinspirasi oleh postingan saya di Threads. Bunyinya kira-kira begini, “Agama adalah mesin pembunuh paling sistematis yang melebihi nuklir. Apalagi ketika agama sudah dipertuhan, seperti yang dilakukan kaum-kaum fanatik yang merasa paling suci dan paling berhak membunuh. Bikin lelah beragama.” Ternyata unggahan pendek ini memancing komentar beragam. Yang melihat pun sampai dua ribu lebih dalam hitungan jam.
Unggahan itu sebagai curahan hati, keprihatinan, sekaligus kemarahan saya selama ini melihat perilaku orang-orang yang mengaku beragama, tapi kelakuannya jauh dari ajaran agama. Agama justru menjadi legitimasi untuk menebar kebencian dan pertumpahan darah. Dengan ajaran yang diperoleh baru di tataran permukaan, kaum-kaum beragama itu lalu berani berjualan ayat demi uang, surga, dan sertifikat halal untuk menghakimi, melakukan persekusi, bahkan kalau perlu membunuh yang tidak sepaham dan sealiran.
Fakta historis yang belum terlalu jauh menjadi contoh dan data nyata betapa agama menjadi sebuah mesin pembunuh yang cukup efektif. Misalnya, organisasi teroris kekhalifahan ISIS sejak 2014 hingga kini sudah membunuh lebih dari 200 ribu orang tak bersalah hanya karena tidak sepaham, tidak sealiran, dan dianggap murtad dan menodai impian negara Islam di Suriah dan Irak. Nyawa binatang jauh lebih berharga dibanding nyawa manusia di mata para teroris berkedok Islam itu. Cara pembantaiannya pun di luar nalar manusia normal. Mungkin grup teroris yang disembah-sembah kaum radikal itu seperti psikopat berjamaah yang haus darah.
Tak hanya itu. Buddha yang dikenal pecinta damai pun menjadi mesin pembunuh di Myanmar ketika mereka membantai kaum minoritas muslim di Rohingya sejak 2017. Lebih dari 700 ribu orang harus lari menyelamatkan diri dari tanah tumpah darahnya. Pembantaiannya pun tak kalah keji. Kaum nasionalis dan agamis beramai-ramai meninggalkan ajaran welas asih dari Sang Buddha dengan pedang dan bedil berlumuran darah.
Di India yang mayoritas Hindu pun tak kalah seru ketika membantai minoritas muslim. Misalnya kerusuhan di Gujarat pada 2002 yang menewaskan lebih dari 1000 orang. Polarisasi dan fanatisme agama telah menjadi alat pembenaran untuk membantai sesama manusia hanya karena beda keyakinan.
Katolik dan Protestan pun tak kalah sadis dalam urusan pembantaian manusia. Coba tengok sejarah di abad-abad kegelapan di Eropa. istilah Abad Kegelapan Gereja lebih mengacu pada periode yang lebih luas di Abad Pertengahan dari sekitar abad ke-13. Gereja saat itu memiliki kekuasaan absolut dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual, bukan hanya terbatas pada konflik Protestan dan Katolik. Lebih dari 10 juta orang terbantai sia-sia di Eropa kala itu.
Ekstremisme agama dianggap sebagai alat untuk merekrut sekaligus menginspirasi kaum radikal untuk melakukan teror. Lihat saja Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, rejim Taliban. Orang menyaksikan bagaimana biadabnya kekejaman mereka. Ideologi agama yang ekstrem telah meringankan tangan mereka untuk seenaknya mencabut nyawa manusia. Tuhannya yang menciptakan pun dikangkangi dengan selalu menyebut namaNya untuk setiap tetes darah yang ditumpahkan dari orang-orang tak bersalah.
Mengapa bisa terjadi?
Jika ditelaah lebih dalam, konflik sektarian bermotif agama atau keyakinan itu bisa ditelusuri penyebabnya. Pertama, agama dianggap sebagai ideologi absolut. Dogma dan doktrin agama dijejalkan begitu rupa sehingga tafsir terhadap teks agama itu ditelan mentah-mentah oleh para pengikutnya. Yang melenceng dari pemahaman itu dianggap murtad dan menistakan ajaran agama. Kaum ekstrem berbasis agama mengeksploitasi pemahaman ini untuk membenarkan kekerasan atas nama perintah tuhan yang diyakininya.
Kedua, politik identitas dan kesukuan. Agama dan keyakinan membuat para pengikut atau pemeluknya makin memiliki rasa identitas yang kuat. Identitas yang menguat ini lalu menciptakan serta memisahkan kata ganti “kita” bagi yang berkeyakinan sama dan “mereka” yang beraliran berbeda. Mentalitas yang memilahkan “kita” dan “mereka” ini ibaratnya menjadi pemicu sekaligus bahan bakar untuk melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Identitas kelompok itu selalu menjadi alasan untuk saling menghancurkan antarkelompok.
Ketiga, eksploitasi persoalan sosioekonomi. Kesengsaraan, kesulitan kehidupan sosial dan ekonomi digunakan sebagai pintu masuk bagi agama. Kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakstabilan ekonomi, politik, sosial bisa dimanipulasi untuk memobilisasi masa dengan mengatasnamakan agama. Kaum ekstrem atau radikal menggunakan narasi agama untuk menyalurkan ketidakpuasan, kekecewaan, frustrasi masyarakat melalui tindak kekerasan. Boko Haram di Nigeria bisa menjadi contoh perlawanan yang mengatasnamakan perjuangan atas nama agama.
Solusi membangun perdamaian
Perdamaian hanya tercapai ketika ada cinta dan penghormatan atas martabat manusia. Keduanya menyaratkan moral yang benar seperti yang diajarkan oleh semua agama. Tapi kadang jauh panggang dari api. Intoleransi dan persekusi selalu mendahului proses perdamaian yang tak pernah mencapai kata damai sesungguhnya.
Sebenarnya ada banyak solusi yang bisa dilakukan untuk membangun perdamaian yang bisa meminimalkan pertikaian berbau agama. Saya hanya mengutarakan beberapa di antaranya saja, yaitu, pertama, dialog antarumat beragama atau antariman. Konsep dialog ini hanya bagus di atas kertas. Itu pun kalau dibaca oleh orang-orang yang punya wawasan dan tataran kesadaran yang sudah matang. Praktiknya, dialog antaragama itu hanyalah retorika dan acara seremonial agar kelihatan rukun secara fisik. Secara batin, siapa yang tahu. Tapi tidak ada salahnya terus dicoba.
Kedua, mencari akar persoalan dari perspektif sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Aspek sosial dan ekonomi cukup penting untuk ditangani. Kemiskinan dan ketidaksetaraan selama ini terbukti selalu menjadi jalan masuk kaum radikal untuk mengeksploitasinya. Pembangunan dan pemerataan sosial ekonomi mungkin bisa menjadi solusi jangka panjang. Orang yang sejahtera taraf hidupnya, aman, nyaman, tidak akan lagi sensitif terhadap soal keyakinan atau agama. Tentu ini masih bisa diperdebatkan.
Ketiga, dan yang penting adalah pendidikan dan upaya menumbuhkan daya nalar yang kritis. Pendidikan tentang kesadaran akan membuat orang makin tahu dan kenal dirinya, terlepas dari keyakinannya. Orang dengan kesadaran akan tahu apa hakikat dan tujuan hidupnya di tengah ciptaan semesta atau Tuhan. Pendidikan tinggi juga tidak berbanding lurus dengan sikap religius yang terbuka. Bahkan makin berpendidikan, makin fanatik dan makin radikal. Sudah banyak contohnya.
Pendidikan harus dibarengi dengan nalar kritis dan kesadaran. Tanpa kedua hal ini, orang tidak berani bertanya dan mempertanyakan kebenaran dari agama yang diyakini. Dengan kesadaran, orang yang mengaku beragama akan terbuka terhadap sebuah keutamaan, kebenaran, pengetahuan, dan cinta. Di level ini, orang akan lebih memahami spiritualitas yang lebih luas daripada agama.
Sayangnya, dunia keagamaan sekarang terbalik. Mereka mengaku sudah tahu persis ajaran agama yang diyakini, padahal hanya kulitnya. Pemahaman artifisial tanpa pernah menembus kedalaman, apalagi sampai penghayatan inilah yang membuat ajaran agama makin terdistorsi oleh para pengikutnya. Dari sana lahirlah fanatisme, radikalisme, ekstremisme agama, sumbu pendek, orang yang mengedepankan kebencian daripada pikiran, okol (otot) daripada akal. Ayat dan dogma seolah bisa memayungi dan membenarkan kelakuan amoralnya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Tak heran kalau agama bisa menjadi mesin pembunuh paling taktis dan berdaya hancur tinggi untuk peradaban manusia yang katanya beradab ini.
Threads saya pikir menjadi sebuah platform teks yang bisa memancing diskusi di kalangan warganet. Tapi yang terjadi justru saya dihujat, dihakimi, dengan komentar yang bikin emosi kalau dituruti. Masih banyak warganet yang bersumbu pendek, tidak mau berpikir, tapi mengedepankan sentimen agamanya untuk berkomentar. Bukan berpikir kritis, tapi malah menuduh saya provokator, atheis, dan sebagainya. Susah memang ketika nalar orang yang terlalu fanatik diajak untuk berpikir dengan kritis. Tapi inilah Indonesia. Negeri yang konon religius, tapi kadang nalar dibiarkan hangus.***
—————
*Tulisan ini adalah pandangan dan pengalaman pribadi penulis.
Oleh Leo Wahyudi S
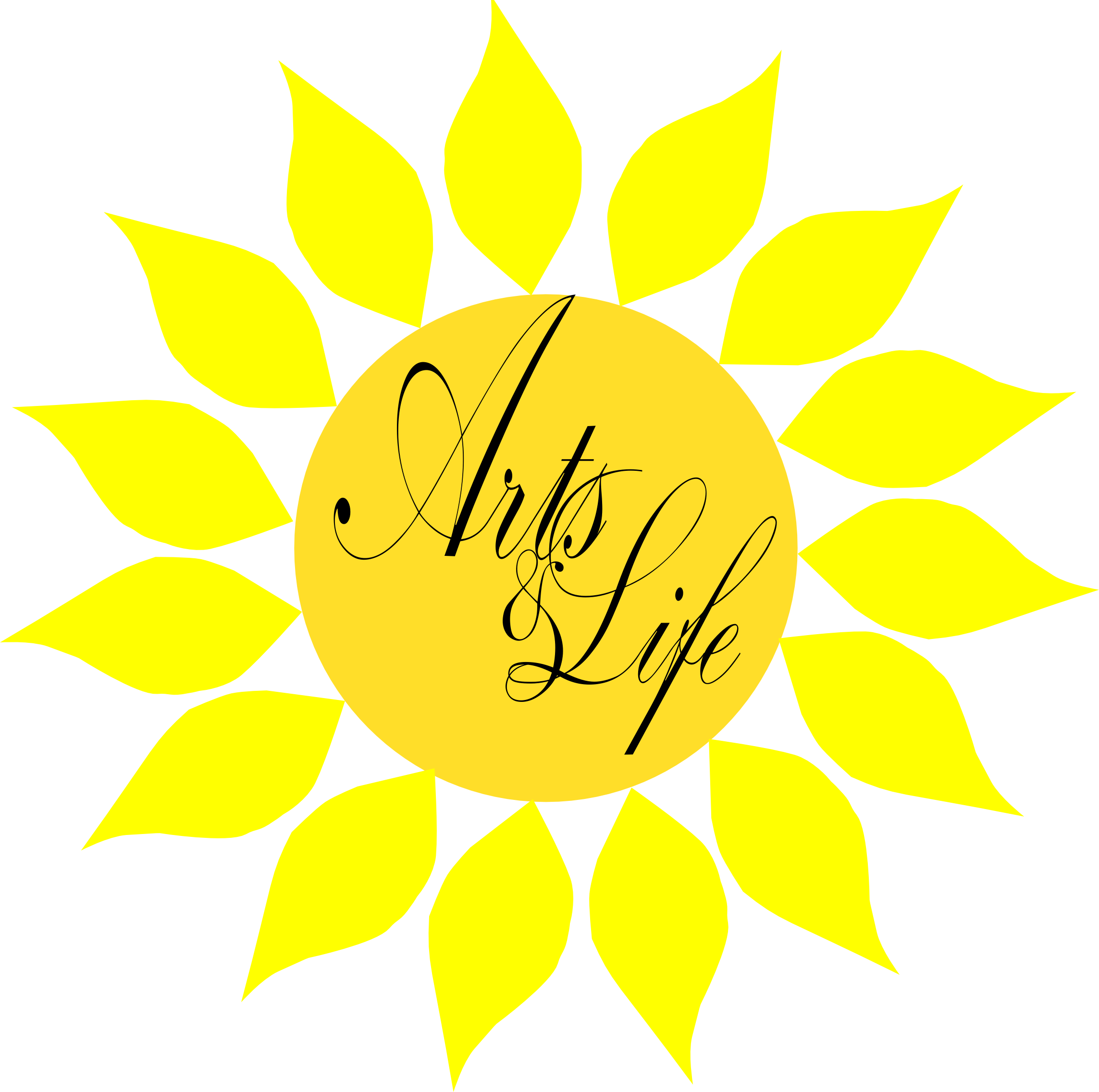

Leave a comment