Kebetulan tiga minggu terakhir ini saya melahap habis enam buku yang rata-rata 200-300 halaman. Semuanya tentang kisah penyintas atau pembelot yang lari dari Korea Utara yang kini hidup di Korea Selatan, Amerika Serikat, atau Kanada. Buku-buku itu merupakan kesaksian atas sejarah hidup dan mati dalam upaya mencari kebebasan dan martabat kemanusiaan.
Buku-buku yang ditulis para pencari suaka dan kebebasan itu nyaris hampir senada, yaitu melarikan diri dari hidup di neraka dunia bernama Korea Utara. Kisah mereka bukan kisah berbunga-bunga dengan bahasa lebay yang hiperbolik, melebih-lebihkan keadaan. Mereka bertutur tentang fakta bahwa nyawa mereka taruhannya. Bahkan sejak kisahnya dibaca di seluruh dunia nyawanya masih terancam oleh rezim keji Korea Utara.
Mereka bersaksi bahwa hidup di bawah rezim komunis Korea Utara adalah dunia kepalsuan, permusuhan, pengkhianatan, kemunafikan, penderitaan, kelaparan, kerja paksa, penyiksaan, pembunuhan, pemenjaraan, pemaksaan. Semua hal yang jahat ada dan nyata dialami oleh warga di negeri itu, sekalipun jaman sudah di peradaban canggih saat ini. Dari usia kecil di bangku sekolah, anak-anak sudah dijejali dan didoktrin dengan kekejaman, loyalitas buta pada negara, kekerasan, kecurigaan. Tak ada hukuman jika ada guru yang memukul muridnya sampai meninggal di kelas, karena guru, tentara, polisi rahasia dilindungi oleh penguasa. Dari kecil anak diajari untuk membenci dan mencurigai, sekalipun itu keluarga sendiri.
Kebanyakan para pembelot ini melarikan diri dari Korea Utara karena alasan pangan dan kekejaman. Rakyat di pedesaan banyak yang mati kelaparan. Anak-anak kecil terlantar ditinggal mati atau pergi oleh orang tuanya. Mereka harus bertahan hidup sendiri, mencari segala hal yang bisa dimakan. Tikus, katak, cacing, ular, ikan adalah kemewahan. Rumput, kulit kayu, akar-akaran beracun yang tak layak makan pun dimakan demi bertahan hidup. Beras menjadi barang termewah yang diimpikan oleh warga non-penguasa di negeri itu.
Seorang pembelot, Shin, bahkan rela mengkhianati ibu dan kakaknya karena mereka mencuri jatah bubur jagungnya. Shin sakit hati. Ia melaporkan kepada polisi kalau ibu dan kakaknya akan kabur dari kamp kerja paksa. Akhirnya ibu dan kakaknya dihukum mati disaksikan oleh Shin. Shin juga disiksa dengan sadis oleh rezim karena bagian dari keluarga penjahat. Hanya karena soal makanan yang sangat langka, kekejian itu terjadi.
Karena kelaparan, dari kecil anak sudah terbiasa untuk mencuri. Hanya demi bisa makan. Mereka menghalalkan segala cara hanya demi sebutir nasi. Mencuri, membunuh, menganiaya, merampok, melacur pun dilakukan. “Orang akan melakukan sesuatu yang di luar pikiran manusia ketika ia kelaparan dan hampir mati. Orang akan menjadi binatang demi bertahan hidup,” kata Yong Kim, seorang bekas tentara yang dijebloskan dalam kamp kerja paksa.
Pembelot lain, Kwang Jin, mengatakan bahwa di Korea Utara tidak ada konsep untuk berbuat baik kepada sesama. Tidak ada cinta, tidak ada agama, tidak ada Tuhan. Yang ada hanyalah pemimpin negara yang dipertuhankan. Menghina, mengotori potret, sang penguasa berarti hukuman mati atau kerja paksa. Bahkan kalau ada kebakaran, potret penguasa lebih penting dari nyawa keluarga. “Saya tidak mengenal cinta tanpa syarat. Yang kita lakukan hanyalah kewajiban keluarga atau karena rasa lapar dan rasa serakah,” katanya.
Orang masih bisa berbicara atau melantunkan lagu soal moral karena mereka belum pernah merasakan kelaparan ekstrem. Tapi saat orang itu mati karena kelaparan, tak satupun orang akan mengingat lagu moral itu. Musuh utama selain rezim militer di Korea Utara adalah kematian itu sendiri. Maka, seberat dan sepahit apa pun hidup, jangan pernah kalah, kata seorang penyintas.
Ada satu benang merah yang saya ambil dari semua buku yang saya baca itu, yaitu memegang kuat harapan agar tetap bertahan hidup. Sesulit, sesakit, selapar, semenderita, apa pun, harapan harus digenggam. Seorang penyintas yang hidup di jalanan sejak kecil, Lee Sung-jung, bahkan mengatakan, “Kau tidak bisa menunggu harapan menghampirimu. Kau harus keluar dan merebut harapan itu.” Ia sekarang tinggal di Korea Selatan, sambil berharap ibu dan kakak perempuannya masih selamat.
Dari kisah-kisah tragis para penyintas untuk bertahan hidup dan keluar dari neraka Korea Utara, kemanusiaan saya sangat tersentuh. Di abad modern ini, manusia tak lebih berharga daripada beras, jagung, dan binatang di negeri komunis itu. Di satu sisi, saya bersyukur hidup di negeri kaya raya bernama Indonesia. Kita selayaknya bersyukur dengan pemerintah dengan sistem yang masih menghormati kemanusiaan. Kita masih bisa makan nasi dan lauk pauk yang luar biasa nikmat. Di Korea Utara, mereka bertahun-tahun makan bubur jagung, itu pun sekali sehari kalau beruntung. Mencari makan sendiri dilarang. Kalau ketahuan dipenjara atau ditembak mati.
Dibanding Korea Utara, Indonesia adalah surga. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan sistem atau pemerintah. Kita masih hidup bebas dan bisa makan makanan yang layak dimakan manusia. Kalaupun sekarang harga beras dan makanan pokok makin mahal, itu tak berarti kita tak bisa makan. Itu akibat rantai pasok dan gagal panen akibat perubahan iklim. Perubahan iklim ekstrem juga buah dari kelakuan manusia yang rakus menguasai sumber daya alam.
Kita hidup di negara merdeka. Tak ada yang disiksa atau dipenjara gara-gara mencari makan untuk bertahan hidup. Pemerintah tidak meneror kebebasan kita. Masih ada keutamaan hidup, masih ada cinta, kebaikan, kepedulian. Ada banyak alasan untuk selalu mensyukuri nikmat, berkah, anugerah dan karunia semesta yang dapat kita nikmati. Mari kita syukuri karena kita hidup di Indonesia.***(Leo Wahyudi S)
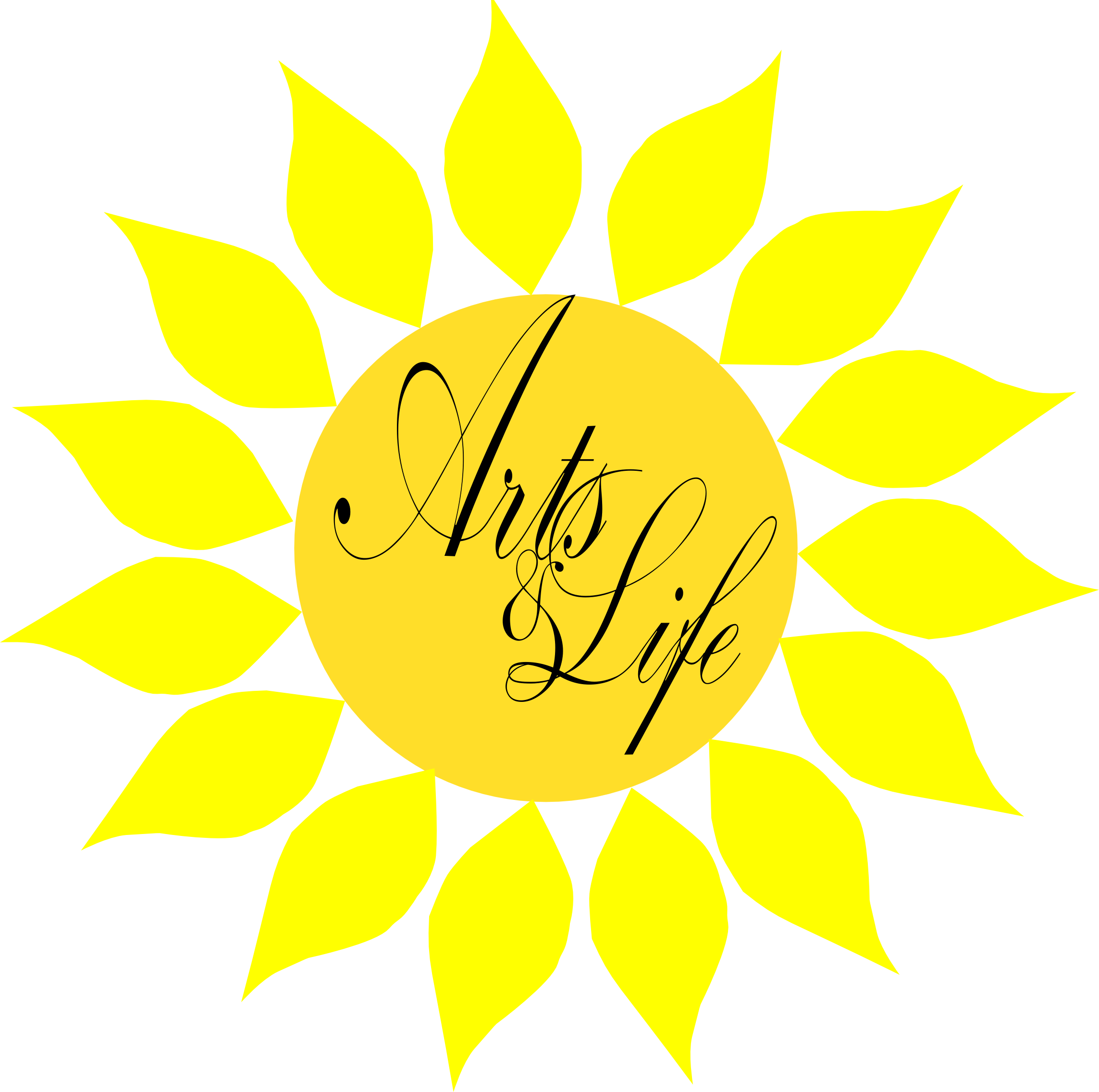

Leave a comment